BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Al-Jarh Wa
Ta’dil
Kata Al-Jarh (الجرح)
merupakan bentuk dari kata Jaraha-Yajrahu (جرح
- يجرح) atau Jariha-Yajrahu (جرح - يجرح) yang
berarti cacat atau luka. Apabila terjadi pada tubuh, ia menyebabkan
mengalirnya darah, dan apabila digunakan oleh hakim pengadilan yang
ditunjukkan kepada saksi, ia berarti menolak atau menggugurkan
kesaksiannya. Sedang menurut istilah Al Jarh berarti upaya
megungkap sifat sifat tercela dari periwayat hadist yang menyebabkan lemah atau
tertolaknya riwayat yang disampaikan. Kata Al Tajrih merupakan bentuk transitif dari
kata Al Jarh yang secara bahasa diartikan menilai cacat. Oleh sebab itu, keduanya
terkadang diartikan sama, yaitu menilai kecacatan periwayat hadist. Sementara
itu dari segi istilah, Al Tajrih artinya memberikan sifat kepada periwayat
hadis dengan beberapa sifat yang melemahkan atau tertolaknya periwayatan.
Secara terminologis, Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib
mendefinisikan Al-Jarh sebagai berikut: “Nampaknya suatu
sifat pada seorang perawi yang dapat merusak nilai keadilannya atau
melamahkan nilai hafalan dan ingatan, yang karena sebab tersebut gugurlah
periwayatannya atau ia dipandang lemah dan tertolak”.
Sedangkan kata Al-Ta’dil (التعديل)
merupakan akar kata dari ‘Addala-Yu’addilu (عدل
- يعدل) yang berarti mengadilkan,
menyucikan, atau menyamakan. Sedang menurut istilah Al-Ta’dil berarti menilai adil seorang periwayat hadis dengan
sifat-sifat tertentu yang membersihkan dirinya dari kecacatan berdasarkan sifat
yang tampak dari luar.
Secara terminologis, Al-Ta’dil dapat didefinisikan juga sebagai berikut: “Membersihkan seorang rawi dan menetapkannya bahwa ia adalah seorang yang
adil atau dhabit”.
Dengan demikian, ilmu Al-Jarh
wa Ta’dil secara etimologis berarti ilmu tentang kecacatan dan
keadilan perawi hadis. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kajian ‘Ilmu Jarh wa Ta’dil terfokus pada penelitian terhadap perawi hadis,
sehingga diantara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai
sifat-sifat keadilan atau kedhabit-an dan yang tidak memilikinya. Dengan tidak
memiliki kedua sifat-sifat itu, maka hal tersebut merupakan indicator akan
kecacatan perawi dan secara otomatis periwayatannya tertolak. Sebaliknya bagi
perawi yang memiliki kedua sifat-sifat di atas, secara otomatis pula ia
terhindar dari kecacatan dan berimplikasi bahwa hadis yang diriwayatkannya dapat
diterima.
Tentang kriteria keadilan
atau ke-dhabit-an perawi, Al-Khatib Al-Baghdadi, misalnya menyebutkan sebagai
berikut: Keadilan dan ke-dhabit-an meliputi: (1) As-Sidqu, kejujuran, (2)
Al-Syarifah bi Thalab Al-Hadis, terkenal dalam pencarian hadis, (3) Tark
Al-Bida’, jauh dari praktek Bid’ah, dan (4) Ijtinab Al-Kabair, bukan pelaku
dosa-dosa besar.
B. Sejarah dan Perkembangan Al-Jarh Wa Ta’dil
Pertumbuhan ilmu Al-jarh wa ta’dil seiring dengan tumbuhnya periwayatan
hadis. Namun perkembangannya yang lebih nyata adalah sejak terjadinya al-fitnah
al-kubra atau pembunuhan terhadap khalifah Utsman bin Affan pada tahun 36 H.
Pada waktu itu, kaum muslimin telah terkotak-kotak kedalam berbagai kelompok
yang masing-masing mereka merasa memiliki legitimasi ( keputusan ) atas
tindakan yang mereka lakukan apa bila mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika
tidak ditemukan, mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu. Sejak itulah para
ulama hadis menyeleksi hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak hanya dari segi matan
atau materinya saja tetapi mereka juga melakukan kritik terhadap sanad serta
para perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Diantara sahabat yang pernah
membicarakan masalah ini adalah Ibnu Abbas (68 H), Ubaidah Ibnu Shamit (34 H),
dan Anas bin Malik (39 H).
Apa yang dilakukan oleh para sahabat terus berlanjut
pada masa tabi’in dan atba’ut tabi’in serta masa-masa sesudah itu untuk
memperbincangkan kredibilitas serta akuntabilitas perawi-perawi hadis. Diantara
para tabi’in yang membahas jarh wa ta’dil adalah Asy-Sya’bi (103 H), Ibni
Sirrin (110 H), dan Sa’id bin al-Musayyab (94 H). Ulama-ulama jarh wa ta’dil menerangkan kejelasan para
perawi, walaupun para rawi itu ayahnya, anaknya, ataupun saudaranya sendiri.
Mereka berbuat demikian, semata-mata untuk memelihara agama dan mengharapkan
ridha dari Allah SWT. Syu’bah Ibnu al-Hajjaj (82 H-160 H), pernah ditanyakan
tentang hadis Hakim bin Zubair. Syu’bah menjawab: “Saya takut kepada neraka”.
Hal yang sama pernah dilakukan kepada Ali bin al-Madini (161 H-234 H) tentang ayahnya
sendiri. Ali bin al-Madini menjawab, “Tanyakanlah tentang hal itu kepada orang
lain”. Kemudian orang yang bertanya itu mengulangi lagi pertanyaannya. Kemudian
Ali berkata: “Ayahku adalah seorang yang lemah dalam bidang hadis”
Para ahli hadis sangat berhati-hati dalam
memperkatakan keadaan para rawi hadis. Mereka mengetahui apa yang harus dipuji
dan apa yang harus dicela. Mereka melakukan ini hanyalah untuk menerangkan
kebenaran dengan rasa penuh tanggung jawab.
Ilmu jarh wa ta’dil yang embrionya telah ada sejak
zaman sahabat, telah berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan hadits dalam Islam.
Beberapa ulama bekerja mengembangkan dan menciptakan berbagai kaidah, menyusun
berbagai istilah, serta membuat berbagai metode penelitian sanad dan matan hadis,
untuk “Menyelamatkan” hadis Nabi dari “Noda-noda” yang merusak dan menyesatkan.
Demikianlah sesungguhnya jarh wa ta’dil adalah
kewajiban syar’I yang harus dilakukan. Investigasi terhadap para perawi dan
keadilan mereka bertujuan untuk mengetahui apakah rawi itu seorang yang amanah,
alim terhadap agama, bertaqwa, hafal dan teliti, pada hadis, tidak sering dan
tidak peragu. Semua ini merupakan suatu keniscayaan. Kealpaan terhadap kondisi
tersebut akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW.
Jarh dan ta’dil tidak dimaksudkan untuk memojokkan
seorang rawi, melainkan untuk menjaga kemurnian dan otentisitas agama Islam
dari campur tangan pendusta. Maka hal itu wajar-wajar saja, bahkan merupakan
suatu keharusan yang harus dilakukan. Sebab tanpa ilmu ini tidak mungkin dapat
dibedakan mana hadis yang otentik dan mana hadis yang palsu.
Pada abad ke-2 H, ilmu jarh wa ta’dil mengalami
perkembangan pesat dengan banyaknya aktivitas para ahli hadis untuk mentajrih
dan menta’dil para perawi. Diantara ulama yang memberikan perhatian pada
masalah ini adalah Yahya bin Sa’ad al-Qathtan (189H), Abdurrahman bin Mahdi
(198 H), Yazim bin Harun (189 H), Abu Daud at-Thayalisi (240 H), dan Abdurrazaq
bin Humam (211 H).
Perkembangan ilmu jarh wa ta’dil mencapai puncaknya
pada abad ke-3 H. pada masa ini muncul tokoh-tokoh besar dalam ilmu jarh wa
ta’dil, seperti Yahya bin Ma’in (w.230 H), Ali bin Madini (w.234 H), Abu Bakar
bin Abi Syaihab (w.235 H), dan Ishaq bin Rahawaih (w.237 H). Ulama-ulama
lainnya adalah ad-Darimi (w.255 H), al-Bukhari (w.256 H), Muslim (w.261 H),
al-Ajali (w.261 H), Abu Zur’ah (w.264 H), Abu Daud (w.257 H), Abu Hatim al-Razi
(w.277 H), Baqi Ibnu Makhlad (w.276 H), dan Abu Zur’ah ad-Dimasqy (w.281 H).
C.
Kegunaan Al-Jarh Wa Ta’dil
Ilmu jarh wa
al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya.
Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa
al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi
yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh
biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kadah jarh dan
ta'dil, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu
ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jarh yang
paling rendah.
Jelasnya ilmu jarh wa
ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu
bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi
"dijarh" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya
harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama
syarat-syarat yang lain dipenuhi.
D.
Metode Untuk Mengetahui
Keadilan dan Kecacatan Rawi dan Masalah-Masalahnya
Dalam uraian yang
baru lalu telah dikemukakan bahwa : menta’dilkan ialah memuji rawi dengan sifat
–sifat yang membawa ke-‘adalah-annya, yakni sifat-sifat yang dijadikan dasar
penerimaan riwayat. Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu
dari dua ketetapan, yaitu :
a. Dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia dikenal sebagai
orang yang adil (bisy-syuhrah). Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di
kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu’bah bin
Al-Hajjaj, Asy-Syafi’I, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Oleh karena itu,
mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu
sehingga tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keadilannya.
b. Dengan pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah), yaitu ditetapkan
sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang dita’dilkan
itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.
Penetapan keadilan
seorang rawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh :
1.) Seorang perawi yang adil, jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya
orang yang menta’dilkan. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan
riwayat (hadist). Oleh karena itu, jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula
untuk menta’dilkan seorang rawi. Demikian menurut pendapat para fuqaha’ yang
mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyah seorang rawi.
2.) Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun
perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak. Selama ia mengetahui
sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.
Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat
ditempuh melalui dua jalan :
1.) Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya.
Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta
dikalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu
sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.
2.) Berdasarkan pentarjihan dari seorang yang adil yang telah mengetahui
sebab-sebabnya dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang oleh para
Muhadditsin. Sedang menurut para fuqaha
sekurang-sekurangnya harus ditarjihkan oleh orang laki-laki yang adil.
Masalah-masalah
yang berkaitan dengan menta’dilkan dan menjarhkan seorang rawi, diantaranya apabila
penilaian itu secara mubham dan ada kalanya mufasar. Tentang mubham ini
diperselisihkan oleh para ulama, dalam beberapa pendapat, yaitu:
1.) Menta’dilkan tanpa menyebutkan
sebab-sebabnya dapat diterima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau
disebutkan semuanya tentu akan menyibukkan saja. Adapun mentarjihkan tidak
diterima, kalau tidak menyibukkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat
berhasil dengan satu sebab saja. Dan karena orang-orang itu berlainan dengan
mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seorang mentarjihkan menurut
keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataan.
2.) Untuk ta’dil, harus disebutkan
sebab-sebabnya, tetapi menjarhkan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta’dilkan
itu bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedangkan mentarjihkan tidak bisa
dibuat-buat.
3.) Untuk kedua-duanya, harus disebutkan sebab-sebabnya.
4.) Untuk kedua-keduanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab si
jarh dan mu’addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut. Di
antara sebab munculnya kriteria mubham dan mufassar karena terjadi perbedaan
pemahaman tentang penilaian terhadap rawi.
Masalah berikutnya adalah perselisihan dalam
menentukannya mengenai jumlah orang yang dipandang cukup untuk menta’dilkan dan
mentarjihkan rawi, seperti berikut ini :
1.) Minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayah.
Demikian pendapat kebanyakan fuqaha’ Madina.
2.) Cukup seorang saja, dalam soal riwayah bukan dalam soal syahadah. Sebab,
bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadist, maka tidak pula
disyaratkan dalam menta’dilkan dan mentarjihkan rawi. Berlainan dalam soal
syahadah.
3.) Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah.
4.) Adapun kalau ke’adalahannya (keadilannya) itu diperoleh atas dasar pujian
orang banyak atau dimashurkan oleh ahli-ahli ilmu, maka tidak diperlukan orang
yang menta’dilkan (mu’addil). Seperti Malik, As-Syafi’iy, Ahmad bin Hanbal,
Al-Laits, Ibnu ‘I-Mubarak, Syu’bah, Is-haq dan lain-lainnya.
E.
Obyek atau Sasaran Al-Jarh Wa Ta’dil
Sasaran pokok dalam
mempelajari ilmu al-jarh wa ta’dil adalah sebagai berikut:
a.
Untuk menghukumi /
mengetahui status perawi hadis.
b.
Untuk mengetahui kedudukan
hadis / martabat hadis, karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis
tanpa mengetahui kaidah ilmu al-jarh wa ta’dil.
c.
Mengetahui syarat-syarat
perawi yang maqbul. Bagaimana keadilannya, ke-dlabitan-nya serta perkara yang
berkaitan dengannya.
F.
Tingkatan Al-Jarh Wa Ta’dil
Ibnu Abi Hatim dalam bagian pendahuluan kitabnya
al-jarh wa at-ta’dil telah membagi jarh dan ta’dil menjadi empat macam.
Masing-masing tingkatan dijelaskan hukumnya. Lalu para ulama telah menambah
lagi dengan dua tingkatan jarh dan ta’dil, sehingga menjadi empat tingkatan,
yaitu:
a.
TINGKATAN
TA’DIL DAN LAFADZ-LAFADZNYA
1.) Lafadz yang menunjukan mubalaghah (kelebihan) dalam hal ketsiqahan
(keteguhan), atau lafadz yang mengikuti wazan af’ala. Contohnya: fulanun ilaihi
al-muntaha fi at-tatsabbut (si Fulan itu paling tinggi keteguhannya), atau
fulanun atsbata an-nas (si Fulan itu termasuk orang yang paling teguh)
2.) Lafadz yang memperkuat salah satu sifat atau dua sifat tsiqah. Seperti,
tsiqatun tsiqah (orang yang sangat-sangat tsiqah), atau tsiqatun tsabitun
(orangnya tsiqah dan teguh).
3.) Lafadz (ungkapan) yang menunjukan ketsiqahan tanpa ada penguatan. Seperti,
tsiqatun (orangnya tsiqah), atau hujjatun (orangnya ahli argumen).
4.) Lafadz yang menunjukan ta’dil tanpa menampakkan kedlabitan. Seperti,
shaduqun (orangnya jujur), atau yang sama kedudukannya dengan shaduq, atau la
ba’sa (orangnya tidak punya masalah –cacat-) yang diungkapkan selain oleh Ibnu
Ma’in, karena kata laba’sa bihi yang ditujukan terhadap rawi dan dikatakan oleh
Ibnu Ma’in mempunyai arti tsiqah.
5.) Lafadz yang tidak menunjukkan ketsiqahan atau tidak menunjukkan adanya
jarh. Contohnya, fulanun syaikhun (si Fulan itu seorang syekh/guru), atau
ruwiya ‘anhu an-nas (manusia meriwayatkan dirinya)
6.) Lafadz yang mendekati adanya jarh. Seperti, fulanun shalih al-hadis (si
Fulan orang yang hadisnya shalih), yuktabu hadistuhu (orang yang Hadisnya
dicatat).
b.
HUKUM
TINGKATAN-TINGKATAN AL-TA'DIL
1.) Untuk tiga tingkatan yang pertama, orang-orangnya dapat dijadikan sebagai
hujjah, meski sebagian dai mereka kekuatannya berbeda dengan sebagian lainnya.
2.) Untuk tingkatan keempat dan kelima, orang-orangnya tidak bisa dijadikan
sebagai hujjah. Meski demikian, hadisnya bisa dicatat dan diberitakan, walaupun
mereka tergolong tingkatan yang kelima, bukan yang keempat.
3.) Untuk tingkatan keenam, orang-orangnya tidak bisa dijadikan sebagai
hujjah. Meski demikian hadis-hadis mereka dicatat hanya sebagai pelajaran,
bukan sebagai sebuah berita (hadis yang bisa diriwayatkan), ini karena
menonjolnya ketidakdlabitan mereka.
c.
TINGKATAN JARH
DAN LAFADZ-LAFADZNYA
1.) Lafadz yang menunjukkan lunak (yaitu yang paling ringan jarhnya).
Contohnya, fulanun layyinun al-hadis (si
Fulan hadisnya linak), atau fihi maqalun (di dalamnya diperbincangkan).
2.) Lafadz yang menunjukkan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, atau yang
serupa. Contohnya, fulanun la yuhtajju bihi (si Fulan tidak bisa dijadikan
sebagai hujjah), atau dla’if (lemah), lahu manakir (dia hadisnya munkar).
3.) Lafadz yang menunjukkan tidak bisa ditulis hadisnya, atau yang lainnya.
Contohnya, fulanun la yuktabu haditsuhu (si Fulan hadisnya tidak bisa dicatat),
la tahillu riwayat ‘anhu (tidak boleh meriwayatkan hadis darinya), dla’if
jiddan (amat lemah), wahn bi marratin (orang yang sering melakukan
persangkaan).
4.) Lafadz yang menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta, atau yang
sejenisnya. Contohnya, fulanun muhtammun bi al-kadzib (si Fulan orang yang
dituduh berbuat dusta), atau muthammun bi al-wadl’I (orang yang dituduh berbuat
palsu), atau yasriqu al-hadis (yang mencuri hadis), atau saqithun (gugur), atau
matruk (ditinggalkan), atau laisa bi tsiqatin (tidak tsiqah).
5.) Lafadz yang menunjukkan adanya perbuatan dusta, atau yang semacamnya.
Contohnya, kadzdzab (pendusta), atau dajjal, atau wadla’ (pemalsu), atau
yukadzdzibu (didustakan), atau yadla’u (pembuat hadis palsu).
6.) Lafadz yang menunjukkan adanya mubalaghah (tingkatan yang amat berat)
dalam perbuatan dusta. Dan ini tingkatan yang paling buruk. Contohnya, fulanun
akdzabu an-nas (si Fulan itu orang yang paling pendusta), ilaihi al-muntaha fi
al-kadzbi (dia orang yang menjadi pangkalnya dusta), hawa ruknu al-kadzbi (dia
orang yang menjadi penopang dusta).
d. HUKUM TINGKATAN-TINGKATAN AL-JARH
1.) Untuk dua tingkatan yang pertama, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh
orang-orang itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi hadis-hadis
mereka bisa ditulis sebagai pelajaran saja, meski mereka itu termasuk kelompok
tingkat yang kedua, bukan yang pertama.
2.) Sedangkan yang termasuk empat tingkat terakhir, hadis-hadis mereka tidak
bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dijadikan
sebagai pelajaran.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ilmu jarh wa at-ta’dil adalah ilmu yang membahas hal
ihwal rawi dengan menyoroti kesalehan dan kejelekannya, sehingga dengan
demikian periwayatannya dapat diterima atau ditolak.
Faidah mengetahui ilmu jarh wa ta’dil ialah untuk
menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus
ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi sudah ditarjih sebagai rawi yang
cacat maka periwayatannya ditolak dan apabila seorang rawi dita’dil sebagai
orang yang adil maka periwayatannya diterima.
Syarat-syarat bagi penta’dil (mu’addil) dan
(jarih):
a. Berilmu pengetahuan
b. Takwa
c. Wara’ (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dosa kecil,
dan makruhat)
d. Jujur
e. Menjauhi fanatik golongan
f. Mengetahui sebab-sebab menta’dil dan mentajrih
Dalam upaya memelihara
keautentikan hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, maka para ulama
terus berusaha dalam menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Dengan cara menilai para
periwayat secara jarh atau ta’dil.
Ilmu al-jarh wa at-ta’dil merupakan suatu ilmu
untuk menyeleksi para periwayat hadis, apakah ia cacat atau adil sehingga hadis
yang diriwayatkannya itu dapat diterima atau ditolak.
Melalui syarat-syarat al-jarh
wa at-ta’dil, lafal-lafal dan kaidah-kaidah tertentu, para ulama hadis menilai para
periwayat dari segi jarh (cacat) dan ta’dil (bersih)nya.
DAFTAR PUSTAKA
https://wilymuhamadr7.blogspot.co.id/2015/10/makalah-ilmu-al-jarh-wa-al-tadil-ulumul.html
https://jacksite.wordpress.com/2007/07/04/ilmu-hadits-al-jarh-wat-ta%E2%80%99dil/
http://novarmandahari12.blogspot.co.id/2013/06/a-pengertian-ilmu-al-jarh-wa-al-tadil.html
http://bukuriau.com/ilmu-al-jarh-wa-al-tadi.html
http://asysyariah.com/al-jarh-wa-at-tadil-upaya-menjaga-kemurnian-syariat/
http://www.avatarzaharuddin.top/2015/02/kaedah-al-jarh-wa-al-tadilserta.html
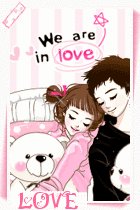



0 komentar:
Posting Komentar